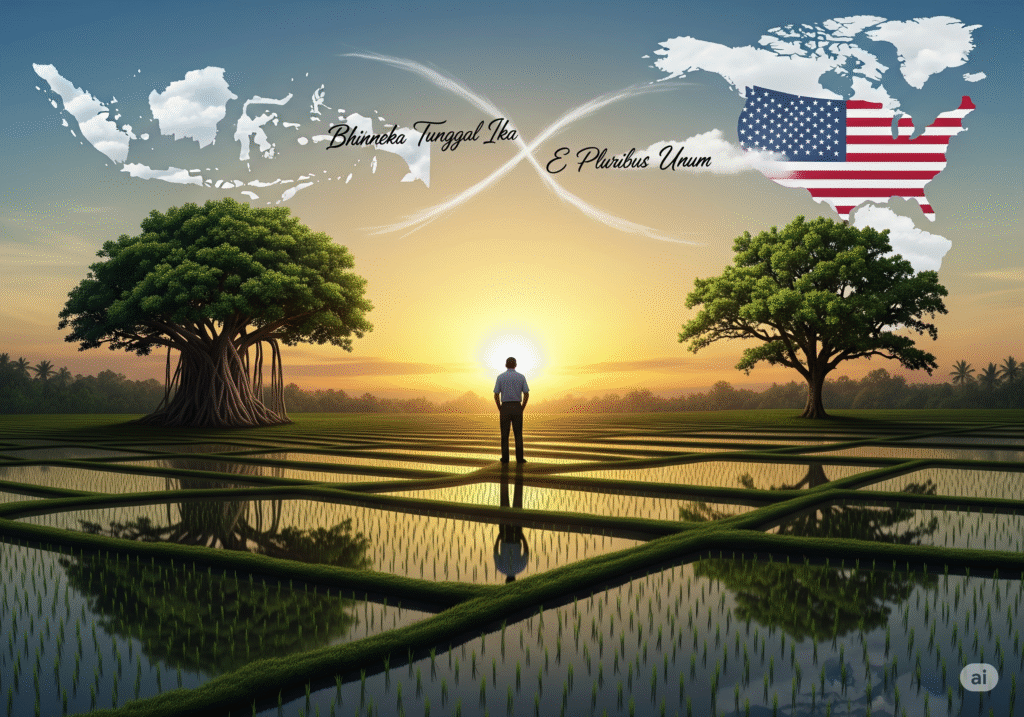Oleh: Abdul Waidl, Pemerhati Sosial Keagamaan
LEBIH dari satu dekade telah berlalu sejak gema tepuk tangan membahana di Balairung Universitas Indonesia pada 10 November 2010. Hari itu, bangsa kita, khususnya generasi mudanya, menyimak dengan saksama pidato seorang tamu istimewa, Presiden Amerika Serikat ke-44, Barack Obama.
Momen itu bukan sekadar kunjungan diplomatik biasa. Itu adalah momen ketika seorang sahabat lama, yang kepingan masa kecilnya terukir di jalanan Menteng, pulang untuk menyapa dan berbagi pandangan. Ia tidak datang sebagai seorang adidaya yang menggurui, melainkan sebagai seorang saksi mata yang melihat Indonesia dari perspektif yang unik: dari luar sekaligus dari dalam.
Membaca kembali transkrip pidato tersebut hari ini, di tengah berbagai dinamika dan tantangan kebangsaan yang kita hadapi, terasa seperti menatap sebuah cermin. Cermin itu memantulkan citra ideal bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Pidato Obama adalah sebuah peneguhan, sebuah afirmasi dari dunia luar terhadap esensi jiwa bangsa kita. Namun, cermin yang sama juga memaksa kita untuk melakukan introspeksi mendalam. Apakah wajah yang terpantul di cermin itu masih utuh? Ataukah ada retakan-retakan yang mulai mengaburkan keindahannya?
Tulisan ini adalah sebuah upaya untuk menelisik pantulan dari cermin tersebut. Sebagai seorang agamawan yang setiap hari bergelut dengan umat, saya ingin mengajak seluruh elemen bangsa, dari para pemuka agama hingga masyarakat umum, untuk merenungkan kembali pesan persahabatan itu dan menjawab sebuah panggilan luhur yang tersirat di dalamnya: panggilan kenabian untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.
Gema dari Seorang Sahabat: Validasi atas DNA Spiritual Bangsa
Hal yang paling menyentuh dari pidato Obama adalah kejujuran personalnya. Ia tidak berbicara dari data intelijen atau laporan diplomatik semata. Ia berbicara dari ingatan seorang anak kecil yang mendengar kumandang azan Subuh berbaur dengan lonceng gereja, yang melihat perempuan bercadar berjalan bersisian dengan mereka yang tidak, yang merasakan kehangatan orang-orang dari berbagai suku dan agama. “Inilah Indonesia,” begitu kira-kira kesaksiannya.
Kesaksian ini adalah sebuah validasi yang luar biasa. Selama ini, kita menggaungkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Kita mengajarkan Pancasila sebagai falsafah hidup. Namun, sering kali hal-hal tersebut hanya berhenti pada level diskursus formal atau hafalan di sekolah. Obama, sebagai seorang “outsider” dengan pengalaman “insider”, mengingatkan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukanlah slogan kosong. Itu adalah DNA spiritual yang tertanam dalam sanubari masyarakat kita. Itu adalah realitas sosio-kultural yang telah hidup dan dihidupi selama berabad-abad, jauh sebelum negara modern Indonesia terbentuk.
Ketika ia menyatakan, “This is the foundation of Indonesia’s example to the world,” ia tidak sedang melontarkan basa-basi diplomatik. Ia sedang membaca potensi terbesar kita. Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi oleh politik identitas, konflik sektarian, dan ketakutan terhadap “yang lain” (the other), Indonesia menyimpan sebuah jawaban.
Jawaban itu adalah kemampuan untuk merayakan perbedaan bukan sebagai sumber perpecahan, melainkan sebagai sumber kekayaan dan kekuatan. Inilah kekayaan hakiki yang kita miliki, sebuah modal sosial dan spiritual yang tidak ternilai harganya.
Sebagai agamawan, kami meyakini bahwa Tuhan menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal (li ta’ārafū). Keragaman adalah sebuah sunnatullah, sebuah keniscayaan kosmis yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Menolak keragaman sama artinya dengan menolak kehendak-Nya.
Pidato Obama seolah menjadi gema dari pesan ilahi tersebut, yang diperdengarkan kembali kepada kita melalui suara seorang sahabat. Ia mengingatkan kita akan harta karun yang kita miliki, yang mungkin terkadang kita lupakan atau bahkan kita sia-siakan.
Menatap Cermin Retak: Realitas dan Tantangan Kebangsaan Kita
Namun, pujian seorang sahabat harus disambut dengan kejujuran dan kerendahan hati. Sambil berterima kasih atas apresiasi tersebut, kita harus berani menatap cermin itu lebih dekat dan mengakui adanya retakan-retakan. Citra Indonesia yang damai dan toleran, sebagaimana yang diingat Obama dari masa kecilnya, kini menghadapi tantangan yang serius.
Pertama, politisasi agama. Ini adalah tantangan terbesar yang mengoyak tenun kebangsaan kita. Agama, yang sejatinya adalah jalan spiritual untuk mencapai kedamaian dan kebenaran, sering kali direduksi menjadi sekadar alat untuk merebut kekuasaan politik.
Ayat-ayat suci dikutip di luar konteks untuk menyerang lawan politik, rumah ibadah menjadi panggung kampanye terselubung, dan sentimen keagamaan dieksploitasi untuk memecah belah masyarakat. Fenomena ini melahirkan polarisasi tajam yang membuat sesama anak bangsa saling curiga hanya karena perbedaan pilihan politik yang dibalut dengan narasi keagamaan.
Kedua, menguatnya kelompok intoleran dan eksklusif. Di ruang-ruang digital maupun di dunia nyata, kita menyaksikan tumbuhnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama namun menyebarkan kebencian, memaksakan kehendak, dan menolak keberadaan mereka yang berbeda.
Mereka membangun narasi bahwa hanya tafsir merekalah yang paling benar, sementara yang lain sesat dan harus dimusuhi. Tindakan persekusi terhadap kelompok minoritas, penolakan pendirian rumah ibadah, dan ujaran kebencian menjadi manifestasi nyata dari ideologi eksklusif ini. Ini adalah penyakit yang jika dibiarkan akan menggerogoti jantung Pancasila.
Ketiga, kesenjangan sosial-ekonomi. Ketidakadilan ekonomi sering kali menjadi bahan bakar yang menyulut api konflik komunal. Ketika sebagian masyarakat merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan keadilan, mereka menjadi rentan terhadap provokasi yang menggunakan isu agama dan suku.
Kemarahan akibat kesulitan ekonomi dengan mudah dibelokkan menjadi kebencian terhadap kelompok lain yang dianggap sebagai penyebab penderitaan mereka. Oleh karena itu, menegakkan toleransi tidak bisa dipisahkan dari ikhtiar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Retakan-retakan inilah yang harus kita akui dengan jujur. Kita tidak bisa terus-menerus terlena oleh pujian dunia luar sementara di dalam rumah kita sendiri, ada pilar-pilar yang mulai rapuh. Mengakui adanya masalah adalah langkah pertama menuju penyembuhan.
Panggilan Kenabian Bangsa: Dari Toleransi Pasif ke Kolaborasi Aktif
Pidato Obama sejatinya bukan hanya sebuah pujian, melainkan sebuah panggilan. Panggilan bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi contoh (example), tetapi untuk menjadi pemimpin (leader) dalam merawat perdamaian dan kemanusiaan global. Untuk menjawab panggilan ini, kita tidak bisa lagi berpuas diri dengan apa yang saya sebut sebagai “toleransi pasif”.
Toleransi pasif adalah sikap “yang penting tidak mengganggu”. Saya dengan ibadah saya, kamu dengan ibadahmu. Kita hidup berdampingan, tetapi tidak saling sapa. Kita tinggal di kompleks yang sama, tetapi tidak pernah bergotong royong. Kita bertemu di pasar, tetapi sebatas transaksi ekonomi. Sikap ini, meskipun lebih baik daripada konflik, sesungguhnya sangat rapuh. Ia tidak membangun jembatan, hanya membiarkan jurang pemisah tetap ada.
Panggilan sejarah bagi kita hari ini adalah untuk bergerak menuju “kolaborasi aktif” atau “toleransi produktif”. Artinya, kita tidak hanya menerima perbedaan, tetapi kita secara sadar dan sengaja menjadikan perbedaan itu sebagai modal untuk bekerja bersama demi kebaikan yang lebih besar: kemanusiaan.
Bagaimana manifestasinya?
Pertama, Kerja Sama Kemanusiaan Lintas Iman: Para pemuka agama dan umatnya harus menjadi garda terdepan. Ketika terjadi bencana alam, jangan lagi ada posko bantuan yang eksklusif berdasarkan agama. Gereja, masjid, pura, dan vihara harus membuka pintunya untuk semua korban tanpa terkecuali. Pemuda masjid dan pemuda gereja bisa bekerja bahu-membahu membersihkan lingkungan, mengorganisir donor darah, atau mengadvokasi isu-isu publik seperti kerusakan lingkungan dan korupsi.
Kedua, Dialog Karya, Bukan Hanya Dialog Kata: Forum dialog antaragama memang penting, tetapi sering kali hanya berhenti di kalangan elite dan di ruang-ruang seminar. Kita perlu membumikannya menjadi “dialog karya”. Mari kita ciptakan ruang-ruang perjumpaan di tingkat akar rumput.
Misalnya, sebuah pesantren mengundang pendeta untuk berbagi tentang etika lingkungan dalam tradisi Kristen, atau sebuah komunitas gereja belajar tentang konsep zakat sebagai instrumen keadilan sosial dari seorang kiai. Perjumpaan otentik inilah yang akan meruntuhkan tembok prasangka.
Ketiga, Pendidikan Kebangsaan yang Transformatif: Sistem pendidikan kita harus direformasi untuk tidak sekadar mengajarkan toleransi sebagai pengetahuan, tetapi sebagai pengalaman. Program pertukaran pelajar antar-daerah dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda, proyek-proyek sosial kolaboratif antar-sekolah yang beragam, serta kurikulum yang secara eksplisit mengajarkan sejarah kontribusi semua agama dan suku dalam membangun Indonesia harus menjadi prioritas.
Inilah esensi dari panggilan kenabian sebuah bangsa. Setiap agama membawa misi profetik (kenabian) untuk menegakkan keadilan, menyebarkan kasih sayang, dan memuliakan kehidupan. Ketika umat dari berbagai agama di Indonesia mampu bersatu padu untuk menjalankan misi profetik kolektif ini, maka itulah saatnya Indonesia benar-benar menjadi rahmatan lil ‘ālamīn, rahmat bagi seluruh alam.
Penutup: Menjawab Panggilan Sejarah
Pidato Barack Obama pada tahun 2010 adalah sebuah hadiah. Ia memberikan kita sebuah cermin untuk berkaca. Kini, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan tersenyum puas melihat pantulan citra ideal kita seraya mengabaikan retakan-retakan yang ada? Ataukah kita akan menggunakan cermin itu sebagai wasilah untuk berbenah diri, memperbaiki setiap kerusakan, dan memoles kembali wajah keindonesiaan kita hingga bersinar lebih cemerlang?
Sebagai bangsa yang religius, kita percaya bahwa setiap peristiwa terjadi atas izin Tuhan. Mungkin, kehadiran dan kesaksian seorang sahabat dari seberang lautan itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita kembali akan takdir luhur kita.
Takdir untuk menjadi rumah yang nyaman bagi semua anaknya, dan menjadi suluh yang menerangi jalan perdamaian bagi dunia. Marilah kita jawab panggilan sejarah ini dengan kerja nyata, dengan hati yang terbuka, dan dengan keyakinan teguh bahwa dalam keragaman, kita menemukan kekuatan dan kebesaran-Nya.
Keterangan: Pidato lengkap Barack Obama dapat dibaca di https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2010/11/10/remarks-president-university-indonesia-jakarta-indonesia